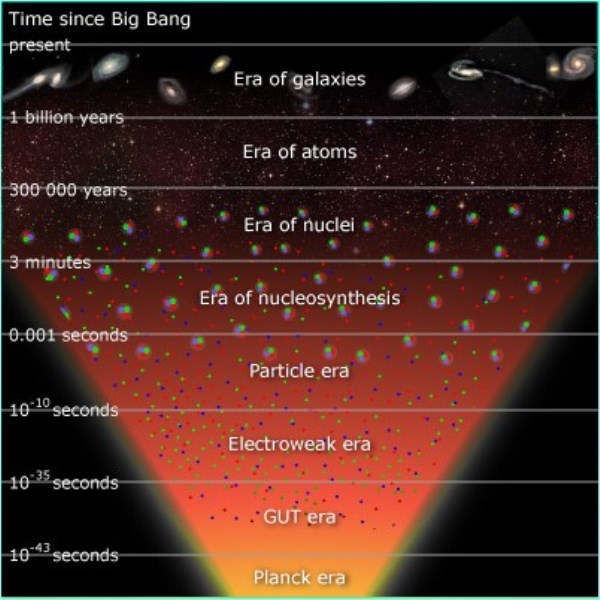Menarik, tulisan Ragil Nugroho, PKS dan Lenin, yang memberi kesimpulan kasar atas pola pengorganisiran revolusioner yang dilakukan oleh Lenin di Rusia, dan menyejajarkannya dengan pola pengorganisiran suatu partai Islam borjuistik (baca: PKS), diapresiasi oleh Martin Suryajaya dengan penalaran filosofis yang berbelit-belit. Dalam tulisannya, Lenin, PKS dan Realisme, Martin terlihat sedang mencari pembenaran dari buku Lenin – Materialism and Empirio-Criticism – untuk memberi sentuhan filsafat pada tulisan Ragil yang kasar; untuk membangun opini pembaca bahwa kritik Ted Sprague atas Ragil adalah keliru; dan juga untuk mencari pengakuan bahwa Ragil adalah seorang realis, atau – meskipun bukan orang yang betul-betul memahami ide-ide Lenin – setidaknya, orang yang mampu mempraktikkan realisme Lenin di lereng Merapi.
Ragil benar-benar tidak memahami maksud Lenin, dan tepat sekali jika Ted Sprague memberinya cap sebagai sang pencolek ide yang kasar dan vulgar. Di dalam tulisannya yang dipublikasikan oleh sebuah jurnal online, Indoprogress, Ragil menulis:
“Bagi yang alergi kekuasaan, ada karya Lenin yang ditulis setelah revolusi Oktober 1917: Komunisme ‘Sayap Kiri’: Suatu Penyakit Kekanak-kanakan. Risah ini ditulis untuk mengatasi jalan buntu ketika situasi tak revolusioner. Saat gelombang revolusi menerjang, dengan mudah orang akan mengangkat tangan kiri. Bila situasi sebaliknya, satu persatu akan meninggalkan perjamuan. Tapi bukan berarti tak terpecahkan. Dalam situasi yang biasa-biasa saja, Lenin menekankan pentingnya partai komunis mengambil strategi bekerjasama dengan kekuatan lain. Dan, bila memungkinkan ikut ambil bagian dalam pemerintahan yang berbasis luas. Artinya, tinggalkan molotov dan batu, untuk kemudian ambil bagian dalam kekuasaan.”
Pada kalimat tengah, “... Dalam situasi yang biasa-biasa saja, Lenin menekankan pentingnya partai komunis mengambil strategi bekerjasama dengan kekuatan lain....”, telah menunjukkan ketidaktahuannya akan maksud Lenin. Baca Selanjutnya
Top ten Real money Online slots games Greatest Position Online game 2024
-
Posts Better Online slots The real deal Currency Considering Reddit Within
the 2023 What is the Finest A real income Harbors App For Android os Mobile
phon...
1 jam yang lalu