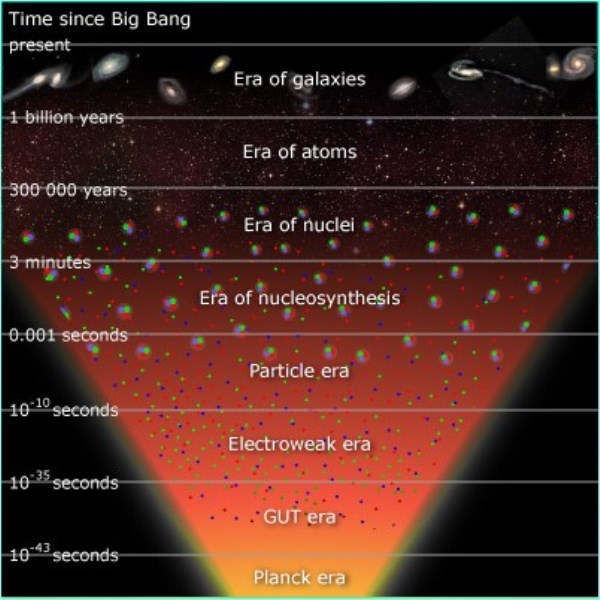“Apakah kelas adalah subjek yang homogen?”; “bukankah dalam kelas juga melekat identitas?”; “jika begitu adanya, bukankah kategori kelas setara dengan kategori identitas?”.
Kali ini, kita akan mendiskusikan poin yang cukup membingungkan, dan karena itu sering membuat kita keliru dalam memutuskan kebijakan politik tertentu, yakni Identitas dalam Kelas. Sederhananya, di dalam kelas sosial tertentu, katakanlah kelas proletariat atau kelas buruh, melekat pada diri anggotanya identitas tertentu, seperti agama, ras, bahasa, gender, suku-bangsa, dan warna kulit. Kita katakan ia adalah bagian dari kelas buruh yang, misalnya, beragama Islam, bersuku Jawa, berkulit sawo-matang, dst, dst.
Dengan statusnya yang demikian, maka pada momen-momen tertentu kesadaran kelasnya, kesadarannya sebagai seorang buruh, tumpang tindih dengan kesadaran identitasnya, kesadarannya sebagai seorang muslim, misalnya. Konkretnya, dalam aksi menuntut kenaikan tingkat upah, perbaikan tempat kerja, atau penghapusan hubungan kerja yang fleksibel, ia bersama-sama dengan seluruh anggota kelas pekerja, tanpa memandang asal-usul identitasnya, berbaris bersama dengan satu suara, satu komando. Atau sebagai petani ia akan berdiri bersama-sama dengan yang lainnya untuk mempertahankan tanahnya yang hendak dicaplok oleh korporasi yang dibeking oleh aparatus negara, tidak peduli identitas mereka apa. Tetapi, ketika terjadi aksi menuntut diadilinya seorang penista agama, maka sebagai seorang muslim ia terpanggil untuk turut terlibat dalam aksi itu. Kesadaran kelasnya tersubordinasi oleh kesadaran identitasnya, sehingga ia merasa berbeda dengan anggota kelas lainnya yang berbeda identitas dengan dirinya. Dan boleh jadi ia akan berhadap-hadapan secara konfliktual di lapangan dengan anggota kelasnya yang berbeda identitas itu.
Apa yang bermasalah dari kondisi ini? Kita tentu tidak bisa menghapuskan atau mengabaikan identitas seorang. Apa yang harus kita lakukan di sini adalah membedakan secara tegas antara Identitas dan Politik Identitas. Identitas adalah sesuatu yang melekat pada diri kita jauh sebelum kita menjadi sesuatu, sebelum seseorang menjadi seorang buruh, misalnya, walaupun mungkin ia lahir dari keluarga kelas buruh. Di sini, kita tidak memiliki alasan secuil pun untuk menolak keragaman identitas ini, bahkan ia harus dirayakan, harus diberi ruang untuk berkembang agar mekar semerbak. Dalam banyak kasus kesadaran identitas ini menjadi pemicu dan perekat aksi-aksi melawan penindasan oleh korporasi dan negara. Misalnya, perlawanan kaum perempuan melawan politik patriarki yang didukung oleh negara. Atau perlawanan masyarakat adat melawan ekspansi perusahaan-perusahaan berbasis sumberdaya alam.
Baca Selanjutnya