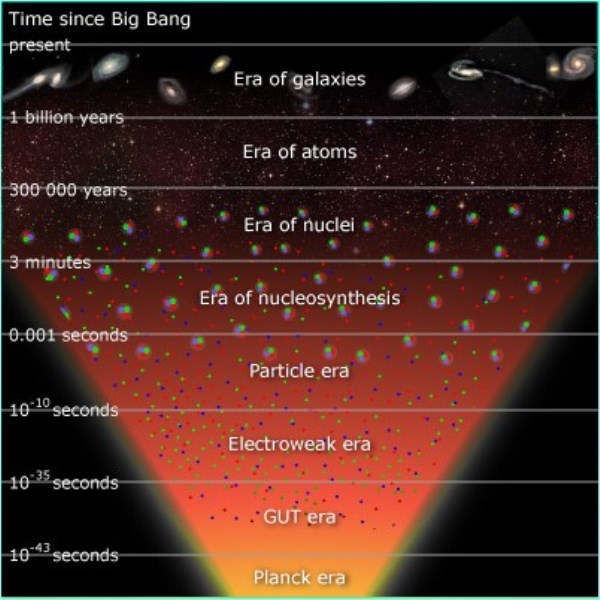Banyak kerancuan timbul dari pemahaman atas konsep Jacques Derrida tentang “pemaafan” (forgiveness). Itu tercermin, misalnya, dari “Maaf”, Catatan Pinggir Goenawan Mohamad (GM) yang baru-baru ini terbit. Tulisan itu mendemonstrasikan kerancuan penulisnya dalam memahami, dan mendudukkan secara “dekonstruktif”, konsep Derridean tentang “maaf”.
Esai Derrida tentang pemaafan yang kerap dikutip adalah “On Forgiveness” (1997), meski terdapat banyak teks lain yang ditulisnya menyinggung problematik itu, dalam satu dan lain cara—salah satunya, “Force of Law: The ‘Mystical Foundation of Authority’” (1990). Dengan membaca teks yang terakhir ini, kita bisa mengetahui mengapa Derrida ingin mengatasi Hukum dan mengejar ketakbersyaratan (unconditionality). Tanpa membaca, setidaknya, dua teks ini secara bersamaan, cara baca kita berisiko myopia, seperti Paktua Goen yang kian pikun.
1. Problematik pemaafan, dalam Derrida, tidak lepas dari problematik keadilan. GM melepas maaf dari pertanyaan tentang keadilan. Argumennya membebaskan Negara dari tuntutan keadilan dan permintaan maaf yang dialamatkan oleh para korban 1965, dan mendorong korban agar memaafkan secara tak bersyarat atas kejahatan Negara. Inilah konsekuensi dari melihat maaf secara terisolir dari problem keadilan. Pandangan ini sangat simplistik, dibandingkan dengan Derrida. Derrida melihat maaf dan keadilan sekaligus sebagai sesuatu yang paradoksal dan kontradiktif, namun harus sama-sama dihitung. Inilah logika “aporia”. Logika ini berlaku baik bagi pelaku maupun korban.
Bagi pelaku: mungkinkah dia meminta maaf, tanpa mengorbankan keadilan yang harus dipenuhinya kepada korban? Bagaimana memenuhi keadilan itu, di hadapan korban yang kehidupannya tak tergantikan dan kebebasannya telah ia renggut? Kritik Derrida, dalam “On Forgiveness”, menyoroti permintaan maaf dari pelaku yang selama ini bersifat seremonial dan basa-basi belaka. Pelaku meminta maaf—dan terkadang memaksa korban untuk memaafkan—namun ia tidak mampu memenuhi tuntutan keadilan. Inilah model permintaan maaf “transaksional”, yang sering dipraktikkan oleh negara-negara untuk mendukung impunitas. Jawab Derrida: tidak mungkin dia meminta maaf; dan kalaupun ia meminta maaf, permintaan maaf itu tak pernah cukup untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Inilah ketidakbersyaratan, dari sisi pelaku. Permintaan maaf harus didorong sampai pada batasnya yang mustahil dan “tak bersyarat”, karena, di hadapan korban, pelaku bukan subjek yang berdaulat. Ia harus tunduk pada imperatif korban, yang tak terbatas, yang tak bersyarat. Baca Selanjutnya
Betfinal 2024 Review
-
Content Gambling enterprise Incentives and Advertisements Betfinal Alive
Never Miss the Live Casino! Do Betfinal Offer Live Betting? We’ll primarily
like g...
1 jam yang lalu